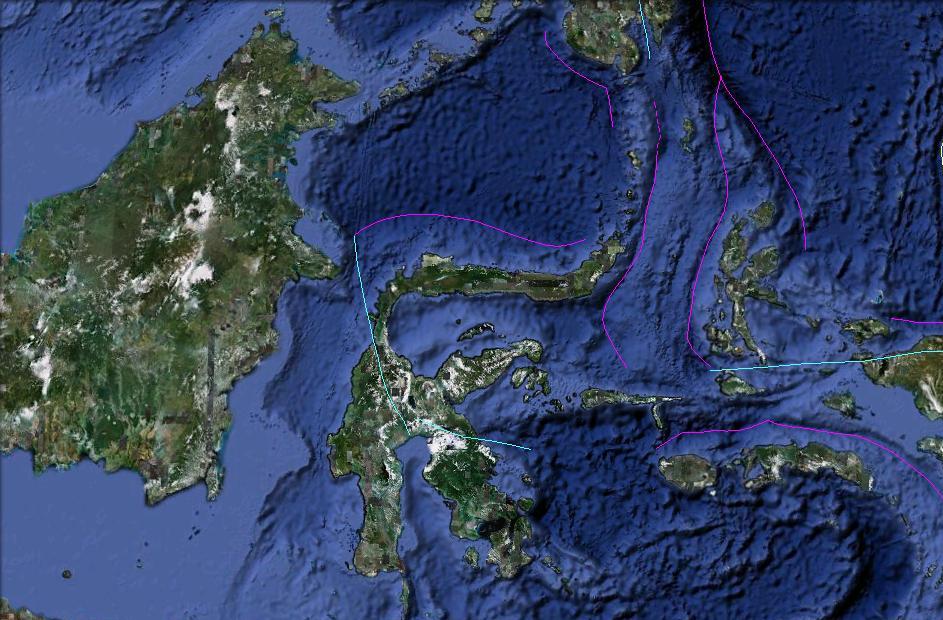Pemerintah Indonesia mengancam akan menghentikan tunjangan jabatan bagi para guru besar yang tidak mempublikasikan riset mereka di jurnal internasional demi untuk mendorong transformasi keilmuan dan inovasi.
Namun sejumlah guru besar menilai pendekatan ini tidak adil tanpa pemerintah lebih dahulu membenahi banyak kendala yang membelit sektor penelitian ilmiah di tanah air.
Hasil evaluasi yang dilakukan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) mengungkapkan dari 5.366 orang professor di Indonesia, sampai akhir 2017 lalu baru 1.551 guru besar atau professor yang memenuhi kewajibannya menulis jurnal internasional.
Sementara sebanyak 3.800 belum menunaikan kewajibannya itu.
Padahal sejak 2017 lalu, berdasarkan Permenristek Dikti Nomor 20 Tahun 2017 Kemenristekdikti telah meningkatkan Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor hingga 3 kali lipat dari gaji pokok sebagai salah satu insentif mendorong produktivitas dosen dalam menulis serta menghasilkan publikasi internasional.
“Guru besar memiliki kewajiban untuk mentransformasi ilmu dan teknologi yang mereka kuasai dan menyebarluaskannya melalui jurnal internasional dan itu artinya mereka harus melakukan penelitian. Tanpa penelitian tidak akan muncul inovasi, tidak aka nada pembaharuan dan Ilmu yang mereka kuasai tidak akan berkembang,” tegas Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek DIkti, Ali Ghufron Mukti.
“Kita tidak ingin para guru besar kita yang sudah mencapai prestasi akademik tertinggi itu terhenti prestasi dan keilmuannya. Jadi perlu terus ada inobasi dan temuan baru yang dapat mengangkat derajat masyarakat dan industri yang saat ini sangat diperlukan,” tambah Ali Gufron Mukti.
Mekanisme sanksi ini baru akan diberlakukan pada akhir 2019 mendatang. Para guru besar yang belum memenuhi kewajibannya hanya diberi waktu 1,5 tahun untuk mematuhi persyaratan ini, sambil pemerintah juga melakukan penyempurnaan seputar aturan ini.
Tidak didukung afirmasi pendanaan
Ketentuan ini ditanggapi beragam oleh guru besar di Indonesia. Prof. Dr. Ir. Dietriech Geoffrey Bengen, DEA, peraih gelar Guru Besar Ilmu Ekologi Pesisir dan Laut Institut Pertanian Bogor sejak tahun 2003 ini menilai pemberlakuan mekanisme sanksi ini tidak adil dan tidak memotivasi riset ilmiah terutama dikalangan guru besar. Ia menyoroti penerapan kebijakan ini yang tidak disertai keberpihakan bagi guru besar.
“Pemerintah sekarang memperketat penilaiannya pada lektor kepala dan guru besar. Jika memang diwajibkan dan hendak didorong untuk melakukan penelitian, harusnya ada keberpihakan. Harus difasilitasi dong. Harus ada afirmasi soal dana penelitian bagi guru besar.
Pada 2016, pemerintah memang telah meningkatkan dana riset atau penelitian di Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan (Kemenristek Dikti) hingga 100 persen. Dari semula hanya Rp 800 miliar menjadi Rp1,53 triliun.
Dan pada tahun 2018, Kemenristek Dikti mengalokasikan dana riset bagi perguruan tinggi negeri sebesar Rp1,29 triliun.
Anggaran yang dikucurkan melalui skema bantuan operasional perguruan tinggi negeri (BOPTN) itu meningkat 22% bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp1,03 triliun.
Namun Profesor Dietriech menilai kenaikan ini belum banyak efektif mengatasi kendala penelitian ilmiah di kalangan guru besar.
“Saat ini untuk mendapatkan dana penelitian dari pemerintah, kami harus berkompetisi dengan semua pengajar baik S-2, S-3 dan dari seluruh Indonesia. Tidak ada dana khusus untuk guru besar. Jadi tidak mungkin semua guru besar dapat kesempatan itu.”
Menurut guru besar yang menyelesaikan pendidikan Doktor (S-3) di Institut National Politechnique de Toulouse, Perancis tahun 1992 dan hingga kini aktif menulis diberbagai jurnal ilmiah dalam dan luar negeri ini, situasi tersebut kian menyulitkan para guru besar di perguruan tinggi yang tidak memiliki program S-3 khususnya perguruan tinggi di Indonesia Timur.
“Kalau perguruan tinggi yang memiliki program S-3, mereka [guru besar] kan bisa membimbing mahasiswa S-3 karena mereka juga wajib mempublikasikan di jurnal ilmiah, sebagai pembimbing namanya bisa masuk karena ikut terlibat. Tapi jika gak ada mahasiswa S-3 mereka harus melakukan penelitian sendiri. Kalau ada afirmasi dana bagi guru besar dan juga kolaborasi riset antar perguruan tinggi, mereka jadi bisa melakukan penelitian.”
Pria kelahiran Sorong, Papua ini juga menambahkan kendala ini juga diperparah dengan prosedur pendanaan yang berbelit-belit dimana hal-hal teknis yang bersifat administratif kerap menyulitkan peneliti.
“Banyak teman mengeluh lebih repot urusan administrasinya ketimbang penelitiannya itu sendiri. Misalnya kita penelitian sampe ke lapangan harus sewa perahu, itu harus ada KTP pemilik perahu itu merepotkan sekali. Seolah-olah kita ini tidak bisa dipercaya. Ini sangat tidak memotivasi.”
Skema waktu khusus
Sementara itu Prof Dr Yayi Suryo Prabandari, Guru Besar bidang kesehatan masyarakat dan keperawatan di Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada (UGM), Yogyakarta, menilai kebijakan yang akan diberlakukan Kemenristek Dikti sebagai hal yang wajar.
“Kalau di luar negeri kalau memang sampai sekian waktu tidak mempublikasikan karyanya kan memang dicabut gelarnya. Jadi suda sewajarnya, ketika sudah dipuncak jabatannya yang paling tinggi, guru besar memang harus memiliki kewajiban untuk membagi ilmunya melalui diseminasi. Baik melalui jurnal internasional maupun artikel populer, karena masyarakat biasa tidak membaca jurnal internasional.”
Namun Ia mengakui tidak adanya skema alokasi waktu khusus bagi guru besar untuk menulis dan mempublikasikan karyanya masih menjadi kendala yang signifikan.
“Kalau diluar negeri seperti di Belanda, dosenkan memang ditanya ya dalam setahun mau mengalokasikan waktu berapa lama untuk riset. Dan ketika melakukan riset mereka memang dibebaskan dari tugas mengajar. Kalau kita disinikan beda. Jadi tugas Tridarma perguruan tinggi yang memang dikerjakan sekaligus, ya kita mengajar, kita menulis dan melakukan pengabdian masyarakat.”
Menyikapi hal ini, wanita lulusan University of Newcastle, Australia dan meraih gelar professor setelah gigih melakukan banyak riset selama 20 tahun terakhir mengenai perilaku hidup sehat dan promosi kesehatan tentang dampak bahaya rokok ini menilai semua berpulang pada kesadaran dan tanggung jawab pribadi guru besar terhadap kewajibannya berbagi ilmu.
“Jadi kita memang harus pintar membagi waktu. Saya pribadi biasanya harus mengambil cuti 1-2 hari khusus untuk menulis jurnal. Dan itu biasanya baru bisa kalau sudah kegiatan mengajar tidak terlalu padat, ketika mahasiswa sudah libur.”
Ia menilai almamaternya sendiri – UGM telah memberikan cukup banyak fasilitas untuk mendukung para guru besarnya menghasilkan publikasi ilimiah.
Mulai dari berlangganan jurnal ilmiah gratis hingga mentoring penulisan jurnal internasional dengan native speaker dari luar negeri. Ia juga tidak menepis fakta insentif tunjangan jabatan professor atau guru besar tidak selalu efektif bagi semua guru besar.
“Terutama guru besar di bidang ilmu yang agak basah, dalam arti mereka bisa menjadi komisaris misalnya, tunjangan profesor itu tidak ada apa-apanya. Jadi insentif bagi mereka tidak terlalu efektif. Ketika mereka sudah senang menjabat yang memang agak susah untuk menulis.”
Jumlah jurnal di Indonesia dinilai masih kurang bagi masyarakat luas. Secara peringkat, Indonesia juga ada di tangga nomor 52 dari total 229 negara. Indonesia masih kalah jauh dibandingkan dengan Singapura.
Kemenristekdikti mengaku metode reward insentif ini sukses mendongkrak jurnal internasional yang ditulis oleh orang Indonesia hingga 300 persen dalam 2 tahun terakhir.
Meski mengalami peningkatan, jumlah pengutipan atas karya-karya itu menurun. Padahal, dikutipnya suatu tulisan ilmiah oleh naskah lainnya merupakan indikator kualitas dari tulisan ilmiah itu.
Pada 2009, ada 19.496 jurnal yang mengutip hasil karya ilmiah peneliti Indonesia. Pada 2010 angka itu turun 20,49 persen menjadi 15.502.
Tahun berikutnya turun lagi sebesar 16,20 persen menjadi 12.990 pengutip. Pada 2012 turun menjadi 9.735 persen atau turun 25,06 persen dari tahun sebelumnya.
Lantas pada 2013 turun lagi jadi 5.772 pengutip atau 40,71 persen. Penurunan tertinggi dan titik paling rendah kualitas jurnal penelitian Indonesia terjadi pada 2014.
Ketika itu, hanya ada 1.388 pengutipan saja, turun drastis 76,04 persen dari tahun sebelumnya. (tempo.co)