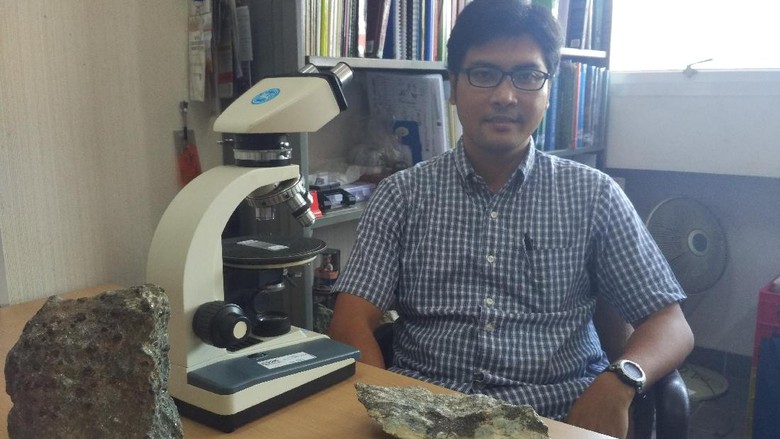JAKARTA – Lahirnya Peraturan Pemerintah No 11/2017, Pasal 239, tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil terkait pembatasan usia pensiun pejabat fungsional madya termasuk peneliti, dari 65 tahun (berdasarkan PP No 21/2014) jadi 60 tahun, telah menimbulkan kontroversi dan gejolak di kalangan para peneliti. Mengapa? Menurut Ismatul Hakim, Ketua Bidang Pemberdayaan Masyarakat Himpunan Peneliti Indonesia.
Pertama, keluarnya PP tersebut ada 516 peneliti dari sejumlah instansi pemerintah— baik kementerian maupun lembaga pemerintahan lainnya— akan terlempar dan dipaksa pensiun dini. Padahal, mereka rata-rata masih produktif dan masih dibutuhkan untuk menghasilkan riset-riset inovatif. Kedua, peraturan ini justru menimbulkan krisis baru di dunia riset, di mana saat ini jumlah peneliti di Indonesia masih terbatas, 9.000-an orang, jauh dari target ideal.
Menurut Iskandar Zulkarnain dalam Rastika (Kompas 27/8/2015), dari sisi jumlah saja, saat ini peneliti Indonesia hanya 90 peneliti per 1 juta penduduk. Bandingkan dengan negara-negara lain seperti Brasil, mencapai 700 orang per 1 juta penduduk; Rusia 3.000 peneliti per 1 juta penduduk; India 160 peneliti per 1 juta penduduk; Korea 5.900 peneliti per 1 juta penduduk; dan China 1.020 peneliti per 1 juta penduduk. Jadi, kalau penduduk China 2 miliar orang, mereka memiliki 2 juta peneliti.
“Kalaupun, toh, dalam PP ini memberikan peluang inpassing yang memungkinkan tenaga struktural bisa beralih menjadi tenaga peneliti, saya pikir ini bukan jalan terbaik. Sebab, untuk menjadi peneliti tidaklah mudah dan tidak bisa seenaknya berganti-ganti profesi. Peneliti itu profesi pilihan yang tidak hanya memerlukan kedalaman kecakapan serta keluasan pengetahuan dan metodologi, tetapi juga karakter dan critical thinking yang kuat,” kata Ismatul
Yang dikawatirkan adalah pintu inpassing ini justru hanya dibuatkan sebagai jalan bagi para birokrat struktural yang sudah atau merasa mentok posisi jabatannya, tetapi miskin daya kritis dan jiwa riset yang kuat. Lebih parah lagi kalau profesi peneliti akhirnya hanya menjadi profesi buangan bagi para pejabat frustrasi, yang akhirnya justru kontra-produktif bagi pembangunan dunia riset kita.
“Saya tidak bisa membayangkan ketika seorang birokrat kemudian langsung beralih profesi menjadi peneliti. Pertanyaannya: apa langsung bisa? Tentunya tidak langsung bisa. Walaupun Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyediakan ruang pelatihan untuk menjadi peneliti, tetapi ini memerlukan transisi waktu yang lama dan energi yang besar karena bergantung dana dan daya tampung dari LIPI itu sendiri,” tambahnya.
Sementara itu, lanjutnya dinamika perubahan dan pembangunan berjalan sangat cepat. Sebab, untuk memasuki era baru persaingan global yang mengandalkan dukungan produk-produk riset yang kuat, ke depan dibutuhkan para peneliti yang andal. (IFR/Dikutip dari Opini Harian Kompas, 23 Agustus 2017 oleh Ismatul Hakim)